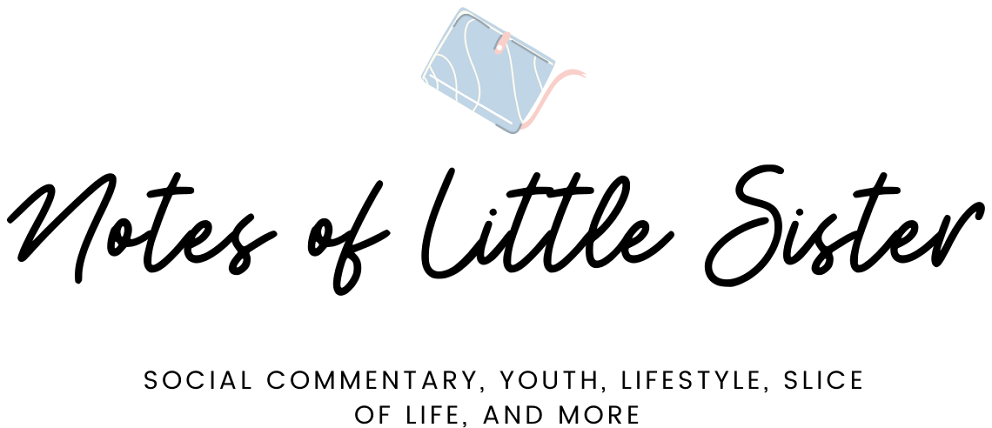Siapa di antara kamu yang sering menemukan postingan quotes tentang mengejar passion seperti gambar di atas?
Gue sering, dan dulu hampir selalu tersihir ketika menemukan kalimat ini di postingan media sosial mana pun. Terdengar powerful dan sangat memotivasi. Tapi sekarang, entah kenapa buat gue kalimat "kejarlah passion-mu" itu terdengar cuma angan-angan, cuma omong kosong. Karena pandangan itu membuat passion seakan-akan menjadi suatu syarat mutlak yang harus kita kejar untuk menentukan arah hidup.
Gue sering banget mendengar atau membaca cerita orang-orang di media sosial tentang bagaimana putus asanya mereka berusaha mengejar passion yang-entah-apa. Bahkan hingga di usia yang terbilang sudah sangat matang, masih banyak yang merasa gagal hidupnya ketika belum tahu apa sesungguhnya bidang yang ia minati. Jenuh sedikit, lantas merasa bukan passion. Gagal di satu bidang, berpikir "mencari" passion adalah solusi atau jawaban.
Kadang kita lupa, hal-hal yang manis itu sifatnya hanya sementara. Passion, yang banyak orang katakan sebagai fondasi hidup juga bisa membosankan dan bikin jenuh pada akhirnya—dan ini pula yang gue rasakan. Passion nggak membuat gue terus bisa menikmati pekerjaan atau hobi yang gue tekuni.
Gue masih sering membanding-bandingkan penghasilan yang bisa gue dapat kalau gue stop pursuing my passion. Hingga akhirnya gue merasa ada yang salah dengan konsep passion yang selama ini gue atau masyarakat kita pahami.
There is no certain passion in life.
Passion nggak hanya ada satu, passion bisa berubah-ubah selama proses kita hidup dan belajar. Passion adalah sesuatu yang abstrak, yang kadang-kadang nggak disadari datangnya ketika kita sudah menemukan itu. Passion juga nggak selamanya sesuatu yang berasal dari dalam diri secara alami, sometimes we have to work on it. Dan once kita menjadikan passion tersebut suatu pekerjaan, it becomes just that, a task we must do. Ini yang gue bilang passion bisa membuat jenuh pada akhirnya.
Lagipula, berbicara soal passion, nggak semua orang punya privilege untuk mengejarnya—bahkan sekadar untuk menyadari bahwa istilah seperti ini ada. Sebagian orang hanya tahu bahwa mereka harus bekerja, mencari uang, dan menabung untuk mendukung finansial dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah kenapa, untuk sebagian orang, terkadang mengejar passion terdengar seperti omong kosong belaka.
Gue teringat dengan statement teman gue yang pernah berbagi opininya soal passion. Menurut dia, passion itu bukan satu profesi atau minat seperti asumsi kebanyakan orang. Namun justru adalah energi yang bikin kita terus hidup dan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terlepas dari berbagai rintangan yang ada. Energi yang membuat kita berani untuk menghadapi rintangan-rintangan baru dan belajar menguasainya. Sebagaimana arti katanya dalam bahasa Indonesia: gairah, semangat, kegemaran, atau keinginan besar.
Passion is the energy that keeps us going, that keeps us filled with meaning, and happiness, and excitement, and anticipation. Passion is a powerful force in accomplishing anything you set your mind to, and in experiencing work and life the fullest extent possible.
Passion adalah energi yang membuat kita terus maju, yang membuat hidup kita dipenuhi dengan makna, kebahagiaan, kegembiraan, dan antisipasi. Passion adalah kekuatan yang sangat besar dalam diri kita untuk mencapai apa pun yang ingin kita lakukan, baik dalam lingkup kerja, hingga kehidupan pada umumnya sampai batas maksimal yang kita bisa.
Ngejar Passion Menghambat Eskplorasi Diri
Selain itu, meyakini bahwa mengejar passion itu adalah satu-satunya solusi atau kunci dari "keberhasilan", juga bisa membuat kita kehilangan ruang gerak untuk eksplorasi. Karena yang ada di kepala kita ya passion ini cuma satu, mutlak. It's like the future goals.
Padahal lagi, yang membawa kita menuju kesuksesan itu bukan hanya konsisten dalam satu bidang, tapi juga keterbukaan, resilient terhadap segala hal baru atau yang akan kita hadapi di masa depan, yang tentunya bisa mendorong kita untuk tumbuh.
Indeed, research has shown that believing passion is fixed can make people less likely to explore new topics—potential new sources of passion.
Rasa enggan untuk eksplorasi karena berpikir belum menemukan passion itu pada akhirnya bisa bikin kitajadi lebih mudah putus asa dalam mempelajari sesuatu ketika menemukan sedikit kesulitan.
Why don't you try to focus on actively developing a passion instead?
Passion Tidak Sama dengan Profesi
Jadi, kalau ada orang yang bilang bahwa passion itu hanya bisa tercapai ketika kita udah berhasil mendapatkan profesi yang diimpikan, menurut gue pernyataan ini kurang tepat. Meskipun kenyataannya, siapa sih, yang nggak merasa passionate dan berapi-api ketika berhasil dapetin pekerjaan yang dia mau? Tetapi tetap aja, energi yang kita punya ini sifatnya fluktuatif.
Waktu gue pindah ke pekerjaan yang baru, di beberapa bulan pertama gue merasa sangat bergairah untuk belajar banyak sekali hal baru dan menantang, sampai di suatu momen dimana gue sadar bahwa tanggungjawab yang gue emban ini cukup besar dan menguras pikiran serta tenaga, perasaan berapi-api ini mulai turun kadarnya. Nggak semenggebu pada saat pertama kali gue on-board.
Tapi, apakah itu artinya gue kehilangan passion, dan harus mencari pekerjaan baru untuk menemukan excitement itu lagi? Nggak juga, sampai sekarang gue masih passionate kok. Passionate karena gue ingin belajar lebih dalam soal pekerjaan gue, bukan karena profesinya.
Dan bukan nggak mungkin hal ini juga yang kamu rasakan. You feel burned out, stressful over the responsibility that you must carry on at work that made you demotivated and want to quit your job ASAP. Maybe it's not the passion that is wrong, but the bad system and time-management that put you on this situation. Passion itu hilang, tapi bukan berarti nggak ada.
Gue paham, seiring dengan meningkatnya kesadaran soal pentingnya work-life-balance di lingkungan sosial saat ini, kita jadi bisa dengan mudah menyimpulkan sendiri perasaan yang kita punya, hanya berdasarkan pendapat mayoritas. Tapi, alangkah lebih baiknya untuk bisa mengenal diri sendiri, sebelum memutuskan apa maksud dari "passion" yang selama ini kita cari.
Apakah yang kamu butuhkan itu sebetulnya suasana baru, atau memang passion alias gairah/semangat/motivasi? Bisa jadi, yang kamu kira nggak punya passion, justru selama ini passion tersebut ada disana. You just don't realize it, karena ternyata yang kamu butuhkan adalah minat baru, suasana baru, tantangan baru untuk mengembangkan passion tersebut.
"When you’re pursuing your passion, it’s important to bear in mind that resilience is key, because the pursuit of passion is an ongoing—and challenging—process."
Referensi: