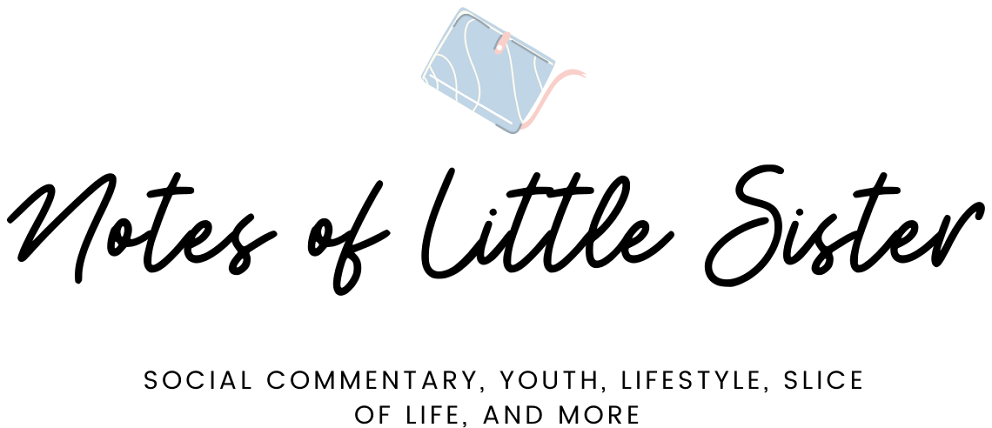Teman-teman, ada yang masih ingat? Lebih dari setahun yang lalu, jagat maya kita sempat dihebohkan oleh pernyataan salah satu influencer yang sempat keblinger freedom of speech, karena mengata-ngatai tubuh seseorang di tempat gym dengan sebutan "polusi visual".
Kemudian setelahnya, muncul lagi pernyataan kontroversial dari MH, seorang model alias "Menteri Kecantikan" yang mengeluh di media sosial pribadinya dikarenakan standard kecantikan Victoria Secret's Angels dan tayangan Gossip Girl favoritnya kini telah bergeser dari yang ia yakini selama ini. Seolah tak kuasa menahan kekesalan, dengan lantang ia melabeli "buriq" seorang perempuan berkepala pelontos dan berkulit gelap yang diketahui sebagai pemeran baru seri Gossip Girl.
Ujaran tidak mengenakan terhadap perempuan yang dianggap tidak memiliki tubuh seperti standard masyarakat juga pernah dialami oleh Nurul, seorang atlet angkat besi sepulang dari Olimpiade Tokyo di Bandara Soekarno-Hatta pada pertengahan Agustus tahun lalu.
Sikap ini seakan-akan semakin melanggengkan eksklusivitas standard kecantikan yang tidak merangkul semua kalangan dan jenis tubuh. Karena itu, gerakan women support women pun tampaknya hanya berlaku untuk lingkaran tertentu.
Pergelutan di media sosial terhadap self-acceptance semacam ini lagi-lagi menunjukan adanya miskonsepsi perihal body positivity. Bagi orang-orang bertubuh "privilege" yang bisa sesuai dengan standard Victoria Secret, gerakan body positivity tampaknya hanyalah bentuk validasi rasa malas bagi orang-orang yang tidak bisa memiliki badan seperti bihun—kurus, langsing, dan berkulit terang. Seakan-akan perjuangan mayoritas perempuan selama berpuluh-puluh tahun tak ada artinya bagi mereka. Padahal body positivity, atau gerakan mencintai dan menerima diri tanpa harus sesuai dengan standard yang berlaku di masyarakat ini sudah diperjuangkan sejak tahun 1960-an di Amerika Serikat.
Asal Usul Kampanye Body Positivity
Kampanye ini berawal dari adanya tindakan diskriminatif terhadap orang-orang yang berbadan gemuk. Fat Acceptance dan Fat Liberation diusung oleh kelompok NAAFA (National Association for Advancement of Fat Acceptance) dan juga feminisme yang aktif di California. Mereka lalu menerbitkan manifesto yang inovatif, dimana isinya ialah menuntut kesetaraan bagi para pemilik tubuh gemuk atau penyandang obesitas dalam seluruh aspek kehidupan. Mereka bahkan menyinggung perihal industri-industri tertentu yang berperan dalam mendukung standard kecantikan dan budaya diet, hingga menyatakan industri ini sebagai musuh.
Gerakan perjuangan inipun terus berkembang pesat. Pada tahun 1980-an, antusiasme terhadap pembebasan orang gemuk dari diskriminasi mulai terus tersebar ke penjuru dunia. London Fat Women’s Group menyusul terbentuk pada pertengahan 80-an dan aktif selama bertahun-tahun.
Orang-orang memang tidak menggunakan istilah Body Positivity pada masa itu, tapi para aktivis yang berperan dalam menyuarakan anti-diskriminasi pada penyandang obesitas ini dapat dengan mudah dijumpai di berbagai acara talk show dan media lainnya. Lalu pada era 90-an, aktivis-aktivis tersebut berdemonstrasi di depan White House, menggelar protes di depan pusat kebugaran yang memajang iklan bernada fatphobic, dan menari-nari bersama rombongan kendaraan pawai pada parade San Francisco’s Pride.
Topik yang kemudian mencuat tentang dorongan mencintai tubuh sendiri ada yang membingungkan beberapa pendengar, namun di saat yang sama juga ada banyak orang yang merasa terinspirasi. Mungkin karena pada saat itu istilah self-love, self-acceptance, dan body positive tidak lazim seperti sekarang. Tampaknya orang-orang ini berpikir bahwa, jika seseorang yang terlihat seperti mereka (dianggap tidak sesuai standard kecantikan) saja bisa belajar untuk mencintai diri sendiri, siapapun tentu bisa.
Baca juga: Childfree yang Diperdebatkan
Hingga memasuki awal 2000-an, internet akhirnya menjadi salah satu platform dimana berbagai bentuk penghinaan terhadap tubuh orang lain dan kampanye tentang mencintai tubuh sendiri mulai banyak tersebar. Meski kondisi tersebut dibarengi dengan munculnya anonimitas (orang-orang yang tidak menunjukan identitas diri di media sosial) dan menyebabkan perundungan, namun kondisi ini tidak dapat terelakan juga menunjukan bentuk ekspresi diri.
Ketika beragam papan pesan dan ruang obrolan tahun 90-an digantikan dengan media sosial, para aktivis ini terus membangun aksinya secara digital. Mereka berpindah dari grup AOL dan forum online NAAFA ke Tumblr dan Instagram. Adanya tagar dan grup-grup Facebook pun membantu banyak orang untuk terhubung dengan cara yang baru. Generasi yang baru ini kemudian menyebarkan aura positif yang dikenal sebagai Body Positivity.
Menerapkan Body Positivity, Tak Mesti Jadi Toxic Positivity
Bagi orang-orang yang memiliki badan lebih kecil dan minim mendapat ejekan seputar kondisi tubuh, mungkin merasa bahwa gerakan body positivity hanyalah bentuk validasi atas rasa malas mereka yang bertubuh gemuk untuk memiliki gaya hidup lebih sehat. Nyatanya, tujuan awal kampanye ini adalah untuk meyakinkan orang-orang bahwa siapapun harus diperlakukan dengan baik, tidak peduli bagaimana bentuk badan mereka, warna kulit mereka, hingga cantik atau tidak rupanya. Toh, segala standard cantik yang berlaku di masyarakat tidak bisa menentukan bagaimana value diri seseorang, dan bagaimana ia berperilaku di lingkungan sekitarnya.
"Lantas, bagaimana kalau para penyandang obesitas atau pemilik tubuh gemuk itu sendiri yang menjadikan ini validasi?"
It's not the campaign that is wrong. It's on them and their mindset. Karena biar bagaimanapun, gue percaya tubuh yang sehat adalah kunci untuk hidup yang juga lebih sehat. Dan gue rasa, mereka sendiri sadar bahwa tubuhnya adalah aset berharga yang mesti dijaga, dirawat dan diberi asupan gizi dengan baik agar bisa bugar hingga tua nanti. Percayalah, gue yang memiliki tubuh kurus pun masih berjuang untuk bisa memiliki hidup yang lebih sehat, dengan pola makan yang teratur dan bergizi. Lagipula, kenapa sih, badan kurus dan langsing harus diasosikan dengan tubuh yang indah dan molek? Apa semua hal yang berkaitan dengan tubuh juga harus dipandang sebagai estetika?
Perlu diingat, bahwa kita bukan patung yang tubuhnya bisa sama rampingnya, bisa dibentuk molek sedemikian rupa, tidak tampak kekurangan sama sekali, tanpa gelambir dan stretchmark disana sini. We have different shapes, sizes, and bone structures.
Tidak semua orang yang kurus hidupnya sehat atau penyakitan, begitupun dengan orang-orang yang memiliki tubuh gemuk. Bisa jadi mereka memang memiliki struktur tulang yang lebih padat dari orang kebanyakan, and that's okay, as long as mereka merawat tubuhnya dengan baik dan sadar akan kesehatan diri sendiri.
Hal ini berkaitan dengan sub-judul yang gue sematkan di atas. Yap, meski body positivity adalah gerakan yang bagus untuk menyadarkan siapapun bahwa setiap orang berhak memiliki citra tubuh yang positif, namun tidak semata-mata kita jadi bisa merayakan obesitas begitu saja tanpa mau mengubah diri sendiri ke arah yang lebih positif. Bukankah sejatinya itu yang dimaksudkan body positivity?
Tidak merawat tubuh kita sebagaimana mestinya dengan mengonsumsi makanan secara sembarangan dan berlebihan dengan dalih body positivity justru akan berdampak buruk bagi diri kita. Inilah yang disebut dengan toxic positivity.
"Duh, ribet banget yaa jaman sekarang terlalu banyak istilah."
Indeed. Tapi menurut gue istilah seperti ini cukup penting untuk diketahui, agar kita bisa lebih mengenal diri sendiri dan tahu kapan waktunya untuk ngerem saat kita sudah terlalu memaksakan prinsip "body positivity" ini.
Dilansir dari Alodokter, toxic positivity adalah kondisi ketika seseorang menuntut dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif serta menolak emosi negatif.
Melihat suatu hal dengan positif memang baik, tapi tidak jika malah mendiskreditkan emosi negatif tersebut, seolah-olah perasaan yang tidak positif adalah sesuatu yang tidak valid untuk kita terima. Karena hal ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental, seperti yang dikutip dari City Nomads di bawah.
Radiating positivity 24/7 is a tough feat for anyone. The pressure to be positive can become toxic quickly. This toxic positivity may not exactly improve one's self or body-image. In fact, may even be counterproductive, because it can manifest as mental health conditions like depression and body dysmorphia, eating disorders and more in the long run.
So, kalau kamu sedang merasa tidak puas dengan kondisi tubuhmu karena berbagai hal, it's okay to feel that way sometimes. Siapa tahu perasaan itu malah mendorong kamu untuk bisa memiliki gaya hidup yang lebih sehat dan teratur. Tapi juga jangan merasa buruk sampai berlarut-larut, karena sesungguhnya setiap orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing.
Believe me, segala standard yang dibangun oleh masyarakat selama ini adalah buah dari kapitalisme. That's why you shouldn't feel guilty about your own body that doesn't fit the beauty standard. Tidak salah juga sebetulnya kalau menteri kecantikan yang gue mention di atas merasa sebal ketika tipe model favoritnya di Victoria's Secret berubah secara inklusif, karena dia hanyalah "korban" dari citra kecantikan yang berusaha dibangun oleh orang-orang di balik Victoria's Secret--the capitalistic marketing itself.
Instead of spending time in front of the mirror criticizing our shortcomings, why don't we use the time we have to examine our strengths and upgrade skills for the sake of our future and our own happiness? Furthermore, we can stop using our bodies to define ourselves and our worth at all. Because our lives isn't only about body and appearance. It's broader than that.
Reference: