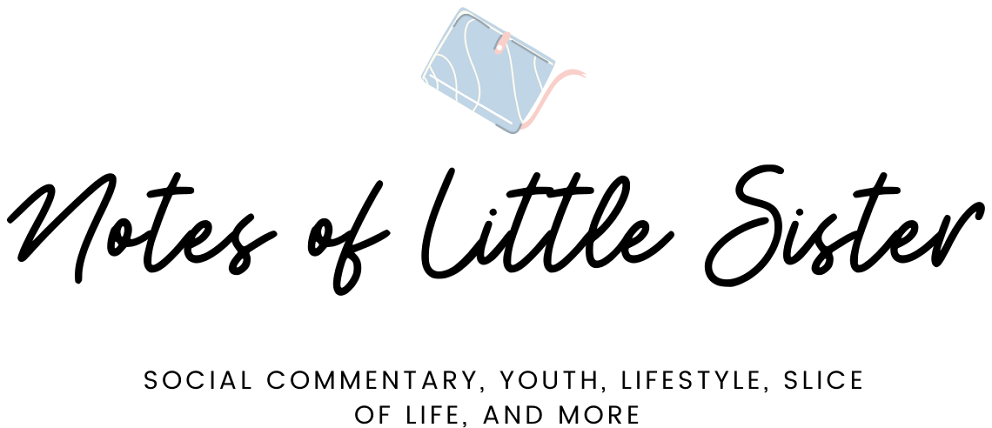Beberapa minggu lalu, gue menulis soal balada pertemanan dan hitam putihnya, yang membuat kita hanya bisa melihat sebuah sisi berdasarkan baik dan buruknya aja. Awalnya tulisan itu singkat, gak sampai satu jam gue selesain. Gue baca-baca dan renungin cukup lama buat gue putuskan apakah ini okay untuk diposting atau nggak, tapi karena ada beberapa statement yang menurut gue terlalu mengutamakan sudut pandang pribadi, gue check and re-check. Ternyata beberapa hal yang gue tulis memang terkesan cukup judgmental dan bahkan menentang akidah.
Dari situ gue berkesimpulan, gue tidak sekritis itu untuk bisa constantly menulis dengan research and data, i'm a human too who's sometimes being too emotional over my perspective. Kemudian permasalahan soal critical thinking jadi berkelebat di kepala gue. Kebetulan sekali sudah beberapa hari ini gue malas buka twitter karena seringnya melihat menfess-menfess yang kebanyakan isinya mempertanyakan hal-hal yang too common dan gak perlu ditanyain alias bisa dicari sendiri. Di satu sisi, gue tahu itulah sebabnya kenapa menfess-menfess ada, gunanya ya buat menciptakan komunikasi lebih dari satu arah dan supaya bisa saling menginform diri. Di sisi lain, gue merasa banyak hal yang bisa kita cari sendiri sebelum kita tanya ke orang lain. That is what google has been created for, right? Tapi ternyata gak semua orang punya inisiatif ini.
Beberapa orang lebih memilih bertanya langsung ke orang lain untuk mengisi lubang-lubang informasi di kepala mereka. Hal ini terlihat sederhana dan mudah, karena kita gak perlu ribet memproses berbagai istilah atau kalimat yang kita temui lewat bacaan. Cukup nyimak penjelasan orang lain, dengerin, perhatiin, udah deh kelar. Padahal kebiasaan ini bikin kita secara gak langsung jadi maunya selalu disuapin, maunya dikasih tutorial, dan buruknya membuat functional literacy kita stuck alias gak ada kemajuan.
Apa sih functional literacy itu?
Functional literacy is the ability to manage daily living and employment tasks that require reading skills beyond a basic level. Artinya, literasi fungsional ini adalah kemampuan untuk mengolah atau menangkap suatu isi dari bacaan, entah itu poster, artikel berita, formulir, job advertisements, dll. Gue yakin kemampuan literasi (the ability to read and write) orang Indonesia itu sebenarnya udah bagus, tapi ternyata gak sedikit yang gak bisa langsung memahami maksud dari apa yang mereka baca. This means, functional literacy-nya rendah.
Hal ini yang bikin kita seringkali harus baca sampai berulang-ulang, dan bahkan harus bertanya ke orang lain yang bisa menjelaskan lebih detail supaya kita bisa ngerti sama isi bacaan tersebut. Nah, functional literacy ini bisa kita tingkatkan dengan melatih critical thinking kita.
Tapi nih, bukan berarti bertanya kepada orang lain itu kegiatan yang jelek, ya. Terkadang malah orang yang banyak bertanya itu sebenarnya kritis. Mereka punya keingintahuan yang besar dan gak malu untuk mempertanyakan hal-hal yang memancing rasa ingin tahu mereka. Sayangnya terkadang ada beberapa situasi dimana seseorang mempertanyakan hal yang sebelumnya bisa dia cari tahu sendiri. Nah, gue pingin ngajak kalian supaya membiasakan diri untuk mandiri dalam berpikir, tapi juga gak malu untuk bertanya tentang sesuatu kepada ahlinya. Bukankah segala sesuatu itu perlu keseimbangan? Koi Fresco said, balance is the key to everything. What we do, think, say, eat, feel, they all require awareness and through this awareness we can grow.
Apa itu critical thinking?
Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir dengan lebih jelas, rasional, dan mampu menganalisis fakta untuk membentuk sebuah penilaian, argumen, atau kesimpulan. Basically, it's thinking about thinking, memikirkan hal-hal tertentu untuk bisa mencapai solusi atau kesimpulan terbaik dalam situasi yang kita sadari. Berpikir kritis bukan berarti cukup dengan mengakumulasikan fakta dan pengetahuan hanya pada satu kali pencarian terus kita bisa pakai itu selamanya. Nggak. Semuanya tentang proses; proses mengumpulkan data dan fakta, dan proses berpikir. Seperti teknologi, setiap dekade pasti selalu ada hal baru yang kita terima karena penelitian gak cuma berhenti pada satu penemuan.
Semakin banyak bacaan yang kita baca, akan semakin banyak kita berpikir, dan proses untuk mencapai kesimpulan akan semakin bijak, karena kita gak asal comot satu sumber buat menuhin isi kepala. Semua itu yang dinamakan berpikir kritis. Oh iya, critical thinking ini adalah metacognitive skill —> a higher level cognitive skill that involves thinking about thinking.
Kenapa sih kita harus berpikir kritis?
Gue akan membagi ini ke beberapa hal, alasan kenapa critical thinking penting untuk kita miliki dan apa keuntungan yang bisa kita dapetin. Pertama, critical thinking bisa memerdekakan cara berpikir kita. Kita bisa lebih mandiri dalam berpikir, tahu mana hal yang bisa diterima mana yang nggak, masuk akal atau nggak, dan nggak terkukung pada inherited opinion; sesuatu yang kita terima dari orangtua, kakek, nenek, atau buyut, misalnya soal mitos kalau duduk di palang pintu bikin kita jauh dari jodoh. Jelas, gue gak mengajari kalian untuk membangkang orangtua, tapi disini maksudnya adalah kita jadi bisa lebih aware akan adanya mitos-mitos dan memiliki keinginan untuk mencaritahu kebenaran di balik itu. Mandiri dalam berpikir ini juga membantu kita terhindar dari yang namanya manipulasi, entah lewat media massa, media sosial, modus penipuan uang atau pyramid scheme (semacam MLM). Otomatis kita pun memiliki opini yang lebih well-informed. Karena kita tau informasi apa saja yang bisa kita terima, meaning kita jadi gak gampang dibodohi oleh berita hoax plus twit buzzer-buzzer gak jelas yang isinya tukang fitnah. Apalagi dalam situasi pandemi kayak sekarang, kelihatan banget kan, mana golongan orang yang berpikir lebih kritis dan mana yang cuma mengandalkan berita dari grup chat whatsapp. Kita seperti lebih ditantang untuk mampu menerima beberapa fakta berdasarkan sains, contohnya diam di rumah karena gak mau menularkan virus kepada orang sekitar, bukan karena lebih takut corona daripada Tuhan. In order to have a democracy and to prove scientific facts, we need criticial thinking in this world. Teori harus didasari oleh pengetahuan, bukan cuma asumsi.
Kedua, kemampuan bahasa dan presentasi kita meningkat. Supaya bisa mengekspresikan diri, kita harus tahu caranya berpikir secara lebih jelas dan terstruktur. Nah, critical thinking also means knowing how to break down texts, and in turn, improve our ability to comprehend. Again, to comprehend, karena basicly berpikir kritis itu adalah tentang memahami apa aja yang kita baca dan dengar, and trying to reduce unimportant things and all noises. Contohnya saat presentasi di depan kelas menggunakan powerpoint, kita akan otomatis terbiasa menjelaskan langsung isi teks yang ada di ppt itu dengan gaya bahasa kita, bukan cuma bacain audiens teks tanpa penjelasan lebih lanjut. Sehingga hal inipun bisa membuat kita tampil lebih percaya diri dan gak perlu takut gak bisa ngomong dan gak bisa mikir pas lagi presentasi atau seminar depan dosen, karena semua hal penting yang kita pahami udah tercatat jelas di luar kepala. Bonusnya, kemampuan public speaking kita bisa lebih meningkat. Interesting!
Selanjutnya, berpikir kritis membuat kita lebih open-minded (kata yang paling terkenal jaman sekarang), artinya sadar dan menerima akan adanya pendapat atau argumentasi lain yang mendukung analisis atau proses berpikir kita. Dalam proses terbukanya pikiran ini, ketika kita mencari tahu dan menemukan banyak fakta, informasi yang datang pasti akan banyak dari setiap sisi. Nah, mengapa kita perlu memiliki critical thinking skill adalah agar kita bisa memutuskan sendiri yang mana yang harus kita percayai. Remember, critical thinking memungkinkan kita untuk memastikan bahwa pendapat kita didasarkan pada fakta dan membantu kita memilah-milah dan membuang bias yang ada. Jadi, buat orang-orang yang udah merasa open-minded, apakah kalian sudah bisa menerima adanya bias dan argumentasi lain atau justru cuma bisa nerima satu fakta baru? Karena yang gue lihat nih, sekarang banyak orang yang ngeklaim diri mereka open-minded tapi cenderung keukeuh sama sudut pandangnya, misal, ada orang yang ngedukung komunitas tertentu dan memperjuangkan hak-hak mereka, tapi di sisi lain gak menerima akan fakta bahwa ada orang-orang yang gak bisa satu suara sama mereka. That's not how your "open-minded" works.
Keempat, critical thinking skill bisa membuat kita berpikir lebih kreatif—definitely. Akan ada banyak sekali ide yang muncul di kepala disebabkan kita yang rajin mengolah informasi dan mencaritahu banyak hal. Pola pikir kreatif ini bisa bikin kita jadi problem solver yang andal. Kedengarannya terlalu iklan, sih, but seriously, lo jadi gak perlu kebingungan untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan kreativitas lebih tinggi karena pikiran lo terbiasa untuk memikirkan dan memilah berbagai hal untuk keluar dari blunder dan menemukan solusinya.
Better decision making, adalah salah satu yang gak kalah penting dalam skill ini. Berpikir kritis membantu kita untuk bisa deal dengan berbagai masalah yang datang dalam hidup kita, karena gak cuma mereduksi berbagai bias dan noises dalam nuance saat berinteraksi dengan orang lain, tapi juga membantu kita mereduksi berbagai pilihan dengan pertimbangan yang matang saat mengambil keputusan. Seringkali untuk memutuskan hal-hal tertentu kita kebingungan sendiri dan bahkan gak percaya dengan diri sendiri. Dalam hal ini, bukan cuma berpikir independen yang dibutuhkan, critical thinking also helps us to trust our gut feeling to make the best choices.
Terakhir dari gue, gak akan bermakna rasanya kalau berpikir kreatif ini gak memberi pengaruh apapun terhadap proses lo memaknai hidup. Without critical thinking, how can we really live a meaningful life? Kita akan sangat membutuhkan skill ini untuk self-reflect dan membenarkan cara hidup kita plus cara kita memandang suatu hal. Indeed, with think, you'll know how to act, tapi itu aja gak cukup. With critical thinking, you know how to have a good life with good actions.
Seperti yang lo lihat, semuanya saling berkaitan dan sebenarnya banyak banget yang belum gue tulis. Tapi intinya udah jelas, betapa pentingnya buat kita memiliki critical thinking, apalagi di era ini. Berpikir kritis gak cuma membenarkan cara berpikir kita dan bagaimana kita memproses berbagai informasi yang diserap, tapi juga bisa membangun kita menjadi pribadi yang lebih bijak, tentunya dengan proses. Seseorang yang dicap kritis dalam berpikir gak selamanya begitu, keterampilan ini bisa memudar kalau kita gak rajin mengasah dan membiasakan. Lama-lama dia akan pudar juga kalau kita menutup diri dari berbagai situasi yang bisa mendorong cara berpikir kita, apalagi kalau kita sengaja melakukan itu karena udah merasa cukup kritis. Eits, jangan. Dalam hal ini, merasa cukup aja gak cukup. Lo harus terus merasa haus supaya lebih banyak lagi pengetahuan yang terkumpul di dalam kepala lo. Anyways, semoga infonya bermanfaat, ya! Kalau ada yang mau nambahin, dengan senang hati silakan masukan di kolom komentar. Gue akan ngebahas gimana caranya berpikir kritis di postingan selanjutnya, stay tuned!☺