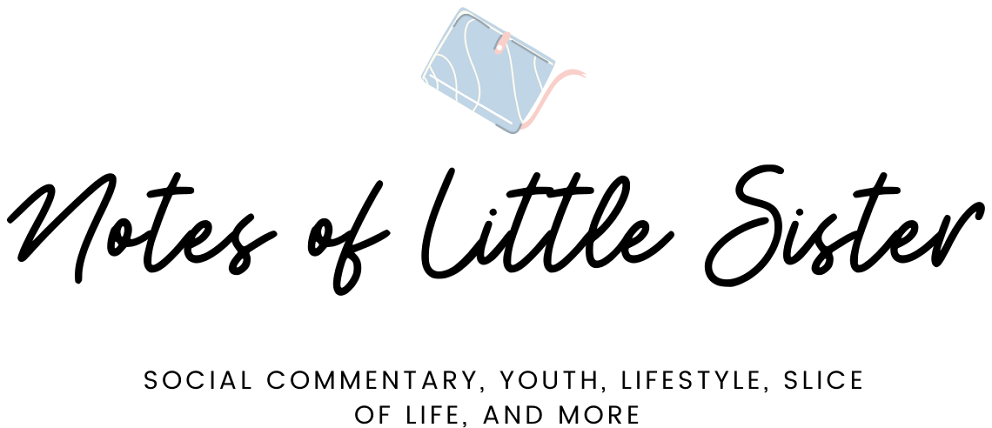|
| Photo by Life Matters from Pexels |
Pertama-tama, sebetulnya gue nggak punya kapasitas yang cukup untuk berkomentar soal ini—ospek virtual adegan marah-marah yang baru-baru ini viral. Namun berhubung gue pernah punya pengalaman di sana, sebisa mungkin gue akan mencoba untuk melihat dari dua sisi. Penulisan tentang ini tergerak setelah gue baca artikel "Merdeka Belajar" Gaya Menteri Nadiem: Apanya Yang Merdeka? yang ditulis oleh Ben Laksana pada Indo Progress. Meski terlihat seperti nggak berkaitan, terdapat tali yang sebetulnya saling berkesinambungan kalau menilik pada konsep dan garis besar pemahaman. Apabila tulisan ini dirasa lebay atau bias bagi beberapa teman mahasiswa, silahkan, bebas untuk menginterpretasikan, kok. Semua yang gue tulis disini murni pendapat gue dan berangkat dari pengalaman serta riset kecil-kecilan di media sosial dan beberapa artikel kependidikan. Jadi, sebisa mungkin gue sudah menjauh dari bias tersebut.
Kedua, sepengetahuan gue, ospek sendiri bisa terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya ospek universitas, ospek fakultas, dan ospek jurusan. Ospek universitas dan ospek fakultas biasanya disatukan dalam rangkaian ospek di awal semester secara umum yang mana tujuannya memang untuk mengenalkan mahasiswa pada kampus, sebagaimana kepanjangan ospek; Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus, meski lagi, hal ini juga tidak bisa disamaratakan karena setiap instansi pasti berbeda kebijakannya, pun dalam hal penamaan. Berdasarkan pengalaman pribadi, keseluruhan ospek di kampus gue sebetulnya termasuk ospek yang sangat menyenangkan, walaupun beberapa aturan semacam harus berangkat pagi buta—bahkan sebelum adzan shubuh—masih dirasa cukup merepotkan. Selebihnya, aksi marah-marah senior dari divisi terkait memang sekadar untuk menertibkan.
Namun masa-masa "dididik" oleh kakak senior yang galak ini berlaku saat ospek jurusan dimulai, yang rata-rata salah satu tujuan diadakannya hal ini bermaksud menyaring anggota baru untuk kepengurusan selanjutnya. Pada bagian ospek jurusan inipun bisa berbeda-beda nama kegiatannya, sebab memang sudah memisahkan diri dari acara ospek universitas. Kegiatan di dalam ospek jurusan tersebut lah yang terbilang cukup keras, setidaknya begitu menurut kesaksian beberapa kerabat dari jurusan dan universitas yang berbeda.
Permasalahan tentang "senioritas", perpeloncoan, dan pembodohan mahasiswa baru dalam setiap kegiatan ospek sebetulnya akan selalu jadi pembicaraan, baik di dalam institusi terkait, maupun pembahasan secara nasional—seperti sekarang—kalau belum juga ada pembaharuan yang dirasa cukup solutif dan adaptif untuk bisa diimplementasikan. Sebagai contoh, di jurusan gue, menjelang penerimaan mahasiswa baru, nggak jarang panitia dari himpunan kami harus gontok-gontokan dengan dosen untuk meyakinkan mereka bahwa acara dalam ospek jurusan ini (re: adanya komdis) bertujuan baik dan segala tindakannya diatur dalam peraturan yang sah secara organisatoris—tentunya peraturan ini berbeda setiap departemen atau instansi.
Adegan marah-marah yang sering disalahpahami inipun sering menjadi fokus utamanya.
"Mahasiswa kok gak kreatif! Masih zaman woy bentak-bentakan?"
"Kita bukan lagi sekolah militer."
"Mental itu gak dibentuk dalam waktu singkat cuma karena bentakan."
Gue sangat setuju, meski gue tahu, tindakan tersebut nggak semata-mata memarahi maba. Sederhananya, mereka ini ingin agar mahasiswa baru tersebut dapat lebih kritis dan punya mental "nggak mau diinjak-injak" supaya si komdis ini bisa dilawan.
Lho, bagaimana bisa?
Iya, memang begitu tujuannya (setidaknya yang gue tahu ya, mungkin treatment setiap kating di univ lain akan berbeda), karena itu gue bisa bilang ini klise. Kenapa klise? Karena pola seperti ini terlalu sering digunakan sehingga membuat tujuan atau makna asli dari hal tersebut pada kenyataannya memudar seiring berjalannya waktu. Sebetulnya konsep pemikiran inipun tergantung pada masing-masing si kakak senior, apakah dia murni ingin "membuat mental dan cara berpikir maba tersebut kritis" atau memang hanya ingin melampiaskan kekesalan mereka saat dibodoh-bodohi senior dulu—kebanyakan sih yang kedua ini kayaknya. It depends.
Namun secara keseluruhan, gue nggak bisa membenarkan bahwa adegan marah-marah yang selama ini melekat dalam kegiatan ospek di tiap universitas di Indonesia adalah sesuatu yang benar dan relevan. Gue melihat rata-rata dari pelaku dan dalang di balik itu terjebak dalam konstruksi berpikir "ospek" yang telah ada sejak puluhan tahun lalu, baik era Soeharto maupun sejak awal era reformasi, yang bahkan memang telah diwariskan sejak zaman kolonialisme dulu. Mereka masih belum tahu apa solusi yang tepat untuk membuat suatu kegiatan ospek dengan tujuan dan misi yang sama, namun berbeda metode. Jadi, pada praktiknya yang dilakukan ya gaya ospek yang seperti itu lagi, itu lagi. Marah lagi, marah lagi. Oleh karena itu, meski beberapa modifikasi perpeloncoan dan "senioritas" telah dihapuskan sepenuhnya di beberapa perguruan tinggi, nyatanya beberapa mahasiswa banyak yang masih terjebak dalam skema "marah-marah dan bentakan" yang dianggap harus ada dalam setiap acara penerimaan mahasiswa baru.
Ospek Tidak Sepenting itu Dalam Perkembangan Nalar Seseorang
Melihat dari serangkaian kasus yang viral beberapa tahun kebelakang ini, dimana contohnya ada beberapa mahasiswa baru dari U** dan beberapa univ lain yang meninggal dan celaka saat ospek, dan ada pula kegiatan dimana maba disuruh merangkak melewati selangkangan seniornya lalu ramai-ramai minum air bercampur ludah, lalu video siswa disuruh makan makanan yang sudah dicampur dalam satu ember secara ramai-ramai (gue lupa liat video ini dimana), sampai ke persoalan marah-marah virtual kemarin, menurut gue ini sudah keterlaluan. Apa bedanya kita sama para diktator dan pemerintah yang sering didemo oleh mahasiswa itu sendiri jika konsep meng-ospek seperti ini masih dipertahankan? Supaya mahasiswa baru ini tahu rasanya diinjak-injak dan memberontak? Supaya mahasiswa yang menjadi agen perubahan ini mampu berpikiran maju dan mendobrak sistem yang bobrok? Begitu?
Konsep seperti ini justru kontraproduktif dengan teori yang telah dikenalkan sejak tahun 1900-an oleh Thomas Lickona bahwa pendidikan karakter mencakup tiga unsur pokok, di antaranya mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (desiring the good) dan melakukan kebaikan (doing the good). Mencoba "membentuk" karakter seseorang dengan cara yang keras untuk menghasilkan reaksi yang bertentangan dengan maksud melahirkan pemikiran yang baik, kritis, dan bijak bukanlah suatu cara yang benar. Bisa saja benar dan berhasil, jika reaksi tersebut mampu dihasilkan oleh maba-maba yang kritis dan "berani" tersebut, bagaimana jika tidak? Bagaimana jika aksi tersebut hanya melahirkan ketakutan-ketakutan baru akan hilangnya kebebasan berpendapat dan malah membentuk generasi yang manut-manut saja, sebab "kebenaran" tersebut telah diakuisisi maknanya?
Jika cara ini dianggap efisien untuk melahirkan "pemberontak-pemberontak" atas sistem yang bobrok, coba kita lihat sejenak. Mereka yang berdiri di kursi pemerintahan sana juga berangkat dari seorang mahasiswa yang kritis dan aktif, dilatih dengan ospek yang katanya lebih keras, tapi apakah hal tersebut menjamin bisa membentuk karakter "pemimpin-pemimpin" ini menjadi lebih progresif dan sadar diri rasanya di bawah? Tidak juga. Bahkan posisinya saat ini kontradiktif, mereka yang dulunya di bawah dan diinjak, berbalik menginjak. Apakah hal ini karena dipengaruhi oleh gaya ospek yang kejam? Tidak juga. Menurut gue, tindakan semacam ini pada akhirnya tidak terlalu mempengaruhi seseorang untuk bertindak sebagai seorang intelek, atau bahkan sebagai bagian dari masyarakat nantinya di dalam kehidupan sehari-hari, karena esensi yang diterima oleh masing-masing anak tentu berbeda.
Dimarah-marahi senior tidak lantas membuat mental kita seperti baja, tidak lantas membuat cara berpikir kita bisa kritis pula, sebab kedua hal ini sifatnya sustainable, yakni terus berkelanjutan selama individu tersebut masih memiliki peran di dalam lingkungannya, dan tentu ada proses panjang yang menggiring kita untuk bisa sampai di tahap tersebut. Bahkan jika seseorang sudah kritis pun, hal tersebut harus selalu diimbangi dengan latihan yang intens. Bagaimana contohnya? Membaca, banyak berdiskusi dan mendengarkan. Latih otak kita untuk berpikir.
Baca juga: Kenapa Perlu Berpikir Kritis?
Mahasiswa-mahasiswa tersebut kemudian seolah hanya menyontek dan menerapkan tindakan tradisional dalam teori tindakan sosial Max Weber, yakni mengamalkan tradisi atau kebiasaan di dalam lingkungan tersebut tanpa perencanaan dan dilakukan secara repetitif, tidak benar-benar mengelaborasi konsep keseluruhan tindakan sosial yang berorientasi nilai, rasional dan afektif.
Senioritas yang Disalahgunakan
Manusia pada dasarnya adalah makhluk individu yang memiliki kebebasan untuk berpikir dan menentukan mana hal yang menurut mereka baik atau tidak, pun jika hal tersebut bertentangan dengan norma, kegiatan ospek yang bergaya militer dan keras (baik secara verbal dan non-verbal) tidak termasuk ke dalam norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sosial. Disinilah kita kemudian perlu membedakan senioritas dan perpeloncoan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan para ahli bahasa, senioritas menggambarkan situasi yang sifatnya perihal junior dan senior (bukan hanya merujuk pada perguruan tinggi) dimana terdapat keadaan seseorang lebih tinggi pangkat, pengalaman, dan usianya; serta prioritas status atau tingkatan seseorang yang diperoleh dari umur atau lamanya bekerja. Sementara perpeloncoan adalah praktik ritual dan aktivitas lain yang melibatkan pelecehan, penyiksaan, atau penghinaan saat proses penyambutan seseorang ke dalam suatu kelompok. Berdasarkan KBBI, aktivitas ini menjadikan seseorang tabah dan terlatih serta mengenal dan menghayati situasi di lingkungan baru dengan penggemblengan, yang jika ditelaah pada kasus-kasus ospek tersebut seringkali dibenarkan dengan dalih senioritas dan adaptasi. Padahal perlakuan dalam ospek yang terbilang keras tersebut tidak selamanya menggambarkan lingkungan baru secara utuh yang perlu diadaptasi oleh mahasiswa baru, dan senioritas itu sendiri kini bergeser maknanya. Sebab tindakan menghargai seseorang atau lawan bicara yang lebih tua dan lebih tinggi secara pangkat, jabatan, pengalaman dan usia tersebut bagian dari norma dan tata krama yang memang sudah semestinya kita terapkan. Sayangnya marah-marah pada ospek ini seringkali hanya dibungkus dengan istilah senioritas.
Mengutip pada artikel dari indoprogress tersebut, nilai-nilai seperti "hierarki, keteraturan, struktur, formalitas, paternalisme dan patriarki" merupakan nilai-nilai kunci dalam upaya rezim Presiden Soeharto yang sebagaimana disebutkan Bourchier dalam bukunya, Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State (2015), terus dilegitimasi oleh negara sampai hari ini, bahkan hingga lingkup universitas sebagai alat ideologi pada ranah pendidikan. Bisa dibilang pola melatih dalam ospek yang terus dinormalisasi seperti ini sama saja dengan mengiyakan tatanan kehidupan yang regresif dan terlalu "kolot".
Hierarki ini digambarkan sebagai senior yang terlalu memposisikan dirinya dan junior sebagai di atas, di bawah, atau mengkategorikannya "pada tingkat yang sama" dengan kategori lain. Keteraturan dan struktur, yang mengarah pada pola didik yang keras yang dapat tergambarkan melalui paternalisme; sistem kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, seperti hubungan ayah dan anak, yang mengungkapkan perilaku superioritas jelas termasuk di dalamnya. Sementara formalitas dapat ditunjukan dengan tujuan klise yang kini menyimpang yang gue sebut pada paragraf sebelumnya, serta patriarki seringkali digambarkan melalui tindakan meremehkan dan menganggap mahasiswi lebih lemah daripada mahasiswa, harus selalu dilindungi dan diayomi seolah perempuan tidak bisa memiliki kendali atas dirinya sendiri. Padahal, tidak sedikit juga perempuan yang justru lebih berani untuk bersuara saat "dimarahi" tersebut.
Perlu diingat, bahwa gue tidak sedang menyoroti kegiatan pada ospek-ospek tertentu secara spesifik, apalagi bermaksud menyinggung. Gue melihat ini secara lebih general yang memang berlaku dalam lingkungan kampus, seperti yang baru-baru ini kembali meruak lewat ospek online di beberapa universitas.
Kekerasan pada ospek ini yang kemudian sama saja membentuk warga negara atau civitas akademika agar tunduk, serta secara sukarela dan secara aktif merangkul nilai-nilai yang telah dibentuk oleh negara—active consent of manufactured consent (Gramsci, 1971; Herman & Chomsky, 2008; Wright, 2010). Strategi atau pola pembentukan karakter ini termasuk menjustifikasi tindakan-tindakan opresif yang dilakukan negara (sebagai aktualisasi nilai-nilai negara) dan melihat hal tersebut sebagai sebuah kewajaran atau "akal sehat" (common sense) dalam keseharian kita. Semua dilakukan demi terwujudnya "kemajuan dan keteraturan" negara di mana definisinya pun telah dimonopoli oleh negara (dalam hal ini kata negara merujuk pada sistem dan pola tindakan kekerasan fisik dan non-fisik yang diberlakukan dalam kegiatan ospek).
Pola asuh otoriter yang diterapkan dalam ospek selama bertahun-tahun sebagai wujud dari hierarki, keteraturan, struktur, formalitas, paternalisme dan patriarki tersebut pada akhirnya hanya akan melahirkan komitmen dan pola pikir yang juga otoriter, sebab sifatnya memaksa untuk tunduk pada aturan-aturan yang telah dinormalisasi, terlepas dari tujuannya baik atau tidak. Lebih dari itu, memaksakan tradisi tanpa inovasi sama saja dengan mengamalkan ideologi Orde Baru yang selama ini dikemas dalam reformasi. Pendidikan bukan lagi bersifat emansipatoris, hanya menurunkan nilai-nilai yang tunduk dan patuh pada sistem negara dan kapitalis.
Gue pikir Revolusi Industri 4.0 yang selama ini dielu-elukan, serta transisi digitalisasi di era pandemi ini bisa membuat perspektif kebanyakan pemuda menjadi lebih progresif dan kreatif, ternyata nggak. Pandemi ini hanya membuat beberapa kelompok terjebak di dalamnya, dan mendaur ulang konsep-konsep yang telah ada sebelum pandemi dengan gaya lebih "kekinian", yakni secara virtual.