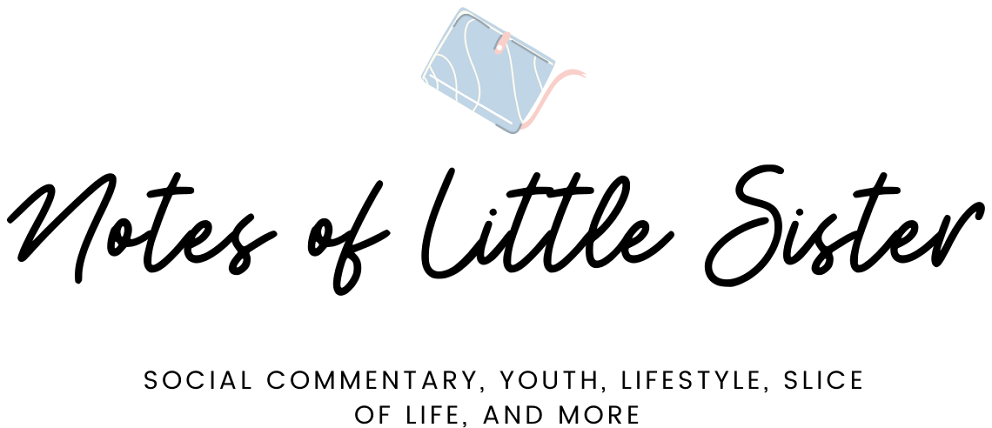|
| Sumber: Territory Studio |
Sebuah serial Netflix yang tayang pada akhir tahun 2021 ini menceritakan tentang dua pemuda asal Berlin di tahun 90-an bernama Carsten Schlüter dan Juri Müller, yang ambisius dan penuh gagasan dalam menciptakan sebuah inovasi pada dunia teknologi, dimana ‘goal’ mereka adalah ingin membawa “dunia” lebih dekat dengan orang-orang melalui jaringan komputer. Demi mewujudkan itu, mereka bersama kawan-kawannya yang merupakan gabungan dari para seniman dan peretas andal kemudian mendirikan ART+COM, sebuah perusahaan rintisan yang mengolaborasikan antara program komputer dan seni digital. Inovasi ini dinamai TerraVision, yang diluncurkan pada tahun 1994.
TerraVision adalah sebuah representasi virtual jaringan bumi berdasarkan citra satelit, bidikan udara, data ketinggian, dan data arsitektur. Aplikasi 3D yang dikembangkan membuat data terestrial terlihat nyata dan dapat dijelajahi secara interaktif. Siapa pun yang menggunakannya dapat bernavigasi secara bebas dalam waktu yang nyata di dunia maya fotorealistik. Yap, jaringan semacam inilah yang kita lihat pada Google Earth saat ini.
Pada era itu, TerraVision menjadi penemuan yang membanggakan saat dipresentasikan pada ajang Konferensi Serikat Telekomunikasi Internasional di Kyoto. Ketenarannya bahkan sampai di telinga eksekutif Silicon Graphics, Brian Andersson yang perusahaannya merupakan pengembang server Onyx terkuat pada saat itu (yang digunakan oleh ART+COM untuk membuat TerraVision). Namun, tak ada yang menyangka bahwa pertemuan mereka dengan Brian pada akhirnya malah membawa ART+COM pada satu masalah besar di kemudian hari.
Selang satu dekade setelah kesuksesan TerraVision, perusahaan Google lalu memunculkan program komputer yang sangat mirip dengan TerraVision. Berbagai konflik akibat dimunculkannya komponen unggulan Google tersebut kemudian membawa Juri dan Carsten pada persoalan hukum yang pelik saat mereka harus memperjuangkan kasus pelanggaran paten atas algoritma yang dipakai pada Google Earth.
Berdasarkan Kisah Nyata
The Billian Dollar Code sebetulnya diangkat dari kisah nyata dan terinspirasi oleh serial biografi Mark Zuckerberg yang berjudul The Social Network. Pada tahun 2014 lalu, ART+COM selaku perusahaan asal Berlin mengumumkan gugatannya pada Google bahwa mereka telah melanggar produk paten AS No. RE44.550, berjudul 'Metode dan Perangkat untuk Representasi Bergambar dari Data Ruang Angkasa,' terkait dengan teknologi Google Earth-nya.
Jika dalam miniseri ini eksekutif SGI (Silicon Graphics) yang berhubungan langsung dengan Carsten dan Juri hanya diwakili oleh Brian Andersson seorang, maka tidak dengan kisah aslinya. Seorang perwakilan ART+COM menyatakan bahwa pada tahun 1995, dalam proses pengembangan TerraVision, penemu mereka sempat bekerja langsung dengan salah dua petinggi Silicon Graphics yang setelahnya diketahui bekerja sebagai CTO Google Earth dan Kepala Bagian Google Maps.
Kala itu, SGI bahkan sempat menggunakan TerraVision sebagai demonstrasi komputer Onyx mereka. Hal ini juga yang memicu ART+COM untuk berani menggugat perusahaan raksasa Amerika tersebut—meski gugatan mereka berujung gagal di pengadilan. Selama proses gugatan, Google mengelak dan menyatakan bahwa mereka menggunakan metode yang berbeda untuk menampilkan gambar beresolusi tinggi agar pengguna bisa memperbesar grafik pada titik tertentu secara spesifik.
Pemuda Naif dan Tempat yang Salah
Dalam serial biografi ini, kita diperlihatkan bagaimana kegigihan dan kejeniusan Carsten dan Juri yang membawa salah satu inovasi dalam dunia teknologi ini seakan berujung sia-sia, karena mereka tidak mendapat kesempatan yang sama untuk bersaing dan berkembang layaknya perusahaan-perusahaan Silicon Valley. Idealisme mereka terdengar seperti isapan jempol bagi para Berliner, sebab pada saat itu banyak masyarakat yang masih skeptis dengan perkembangan internet dan kemungkinan kontribusinya di masa depan, sehingga banyak investor yang menertawai ide brilian Carsten dan Juri.
Salah satu adegan yang membuat kita meringis adalah saat mereka berusaha menjelaskan proposal tentang ide membuat monitor kecil di kursi pesawat, namun lantas diremehkan oleh perusahaan yang mereka datangi. Faktanya, monitor LCD saat ini menjadi fitur yang ada di kursi pesawat.
Tampaknya, bagi mereka ART+COM hanya kumpulan anak muda yang naif dan tidak realistis seperti anak kecil yang bercita-cita menjadi astronot. Pada akhirnya, impian ART+COM untuk bisa mengembangkan TerraVision menjadi lebih dari sekadar peta visual, dan mengganti semua perangkat kerja fisik ke internet pun tidak dapat terealisasikan. Mungkin kenyataannya ide gila puluhan tahun lalu ini memang terjadi, tapi tidak melalui sentuhan ART+COM.
Seandainya saja Carsten dan Juri memutuskan untuk berkarir di Silicon Graphics menjadi anak buah Brian saat itu, mungkin mereka tidak perlu merasakan ditolak berkali-kali oleh investor. Namun, jika begitu mungkin saja mereka tak benar-benar mengerti arti dari sebuah perjuangan. Toh, meski mereka tertinggal selangkah dari Brian yang memiliki privilese di bawah Silicon Valley, dan meski perusahaan mereka tidak sebesar Google, TerraVision tetap memiliki nilainya tersendiri dan menjadi satu-satunya karya yang berharga di tangan ART+COM.
Pada dasarnya, Carsten dan Juri hanyalah anak muda yang penuh dengan ambisi dan inovasi. Sayang cita-cita dan ketulusan mereka untuk mendirikan Silicon Valley versi Berlin tidak disambut baik oleh rekan sebangsanya sendiri.
Jadi, apakah TerraVision benar-benar disabotase? Benarkah Google Earth betul-betul merupakan hasil sabotase TerraVision?
Berdasarkan bukti-bukti yang dimunculkan melalui wawancara karyawan ART+COM dalam tayangan behind the scene, Google Earth dan TerraVision jelas memiliki kemiripan, hanya modifikasi dan rentang usia yang terlihat membedakan.
Namun, salah seorang mantan karyawan yang pernah bekerja untuk EarthViewer (sebelum Google Earth) mengaku bahwa sebetulnya TerraVision bukan satu-satunya perusahaan yang mengaku sebagai penemu algoritma Google Earth. Bahkan algoritme TerraVision dianggap tidak cukup efisien untuk membuat lompatan ke PC—sesuatu yang justru ia dan tim KeyHole kembangkan saat itu. Meski pertanyaannya berakhir sama, apakah mereka tetap menggunakan algoritma TerraVision dan meningkatkannya agar dapat diterapkan pada PC secara lebih efisien?
Kasus gugatan pelanggaran paten inipun bukan satu-satunya yang pernah terjadi. Beberapa di antaranya ada gugatan dari Authors Guild, sebuah Asosiasi Penerbit Amerika mengenai kasus pelanggaran hak cipta dalam pengembangan database Pencarian Buku Google. Ada juga kasus pengadilan Perfect 10 vs Google dimana Google dituntut untuk berhenti membuat, mendistribusikan gambar Perfect 10, dan menghentikan pengindeksan ke situs yang menghosting gambar tersebut, dan masih banyak lagi kasus pelanggaran yang dilayangkan oleh perusahaan minor lainnya.
Harus kita akui, keaslian menjadi sesuatu yang berharga sekali dalam perkembangan era digital. Tak banyak perusahaan yang bisa menelurkan gagasan-gagasan yang autentik. Pada dasarnya pikiran-pikiran kita dapat terhubung satu sama lain karena dipengaruhi oleh lingkungan dan kemajuan di berbagai sektor. Begitu juga yang terjadi pada Juri dan Carsten dua dekade lalu. Mungkin saja saat itu mereka bukan satu-satunya anak muda yang bermimpi tinggi tentang membuat representasi virtual bumi, karena masuknya teknologi datang pada saat yang bersamaan.
Namun, apakah itu artinya boleh “mencuri” ide orang lain untuk kepentingan diri sendiri? Tidak juga. Bagaimana pun, tak ada yang bisa dibenarkan dari tindakan Brian. Sekalipun dalam etika bisnisnya mengambil ide seseorang untuk kemudian dimodifikasi merupakan sesuatu yang wajar, jelas hal ini tidak dapat dinormalisasi—semestinya.
Sang Agen Perubahan
Dari cerita yang separuhnya telah difiksionalisasi ini, semangat juang dan ambisi Juri dan Carsten muda mengingatkan saya pada slogan “agen perubahan” yang selalu disematkan kepada anak-anak muda. Dulu, saya agak skeptis dengan motto ini. Karena realitanya banyak ide-ide baru yang tidak bisa diimplementasikan secara penuh karena hambatan kapitalisme dan ageisme (diskriminasi usia).
Namun pada akhirnya saya juga tersadar, bahwa kehadiran berbagai platform digital saat ini tidak lepas dari ide-ide jenius para pemuda seperti Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Steve Shih Chen, William Tanuwidjaya, Nadiem Makarim, Achmad Zaky, dll. ART+COM mungkin memang bukan salah satu di antara mereka, tapi penemuannya tetap memberi kontribusi yang besar dalam sejarah perkembangan teknologi. Dan tentu saja, perjuangan mereka tidak ada yang sia-sia. Terlebih jika algoritmanya benar telah dicuri, maka kita sudah tahu apa dan siapa yang mendasari lahirnya program Google Earth yang begitu keren saat ini.
Ah iya, omong-omong, judul Billion Dollar itu sendiri mengartikan total keuntungan (sebesar 700 juta dollar) atas algoritma yang selama ini diterapkan pada Google Earth yang mungkin bisa ART+COM dapatkan jika Google mengakui tuduhan pelanggaran paten tersebut. Nilai yang sangat fantastis, bukan?